Hari itu 27 November 1996

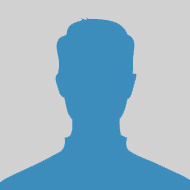
Penulis : Ibnu Siena
8 Juni 2016 19:30
Malam yang bersahabat. Terlentang sekujur tubuhku di atas tempat tidur. Menatap langit-langit kamar. Pukul tiga dini hari. Tapi pikiranku tak bersamaku. Pikirku berada jauh melayang ke sana. Ke-19 tahun lalu.
Aku merasakannya. Seperti pejuang dengan perjuangannya. Seperi penguasa seperti kekuasaannya. Serta lelaki seperti kejantanannya. Merasakan terbang di pelataran surga yang luas beserta se-isi sejuta tanaman dan bintang. Meski saat itu terlalu dini untuk aku rasakan. Ini bukan sebuah takdir. Ini adalah kecelakaan moral paling dahsyat yang disebabkan didobraknya segala batasan-batasan nurani.
***
"Aku jemput kamu jam delapan di tempat yang kita janjikan kemarin, ya."
"Oke," balasnya cepat.
Sebelumnya aku belum pernah bertemu dengan perempuan itu, aku hanya sempat diperkenalkan dengan salah satu teman kuliahku. Aku hanya berkomunikasi melalui pesan singkat, dan hanya butuh waktu tiga hari sebelum aku membuat janji bertemu.
Sesampainya aku di rumah, aku langsung bergegas memacu Honda NSR pemberian ayahku, dua bulan lalu. Aku menelusuri malam dengan penuh rasa tanya: Seperti apa perempuan yang aku temui nanti? Bagaimana aku harus memulai percakapan dengan dirinya? Topik apa yang harus aku bahas dengannya?
Selama perjalanan tak henti-hentinya aku memandang kaca spion kiri untuk memastikan bahwa rambutku tak berubah model akibat tertiup angin. Tetapi tetap saja, aku tak bisa melawan alam. Malam itu, angin bertiup cukup kencang. Rambut yang kusisir rapi, belah pinggir, berantakan sudah. Semoga bukan pertanda awal yang buruk.
Hanya sekitar 20 menit untuk sampai tempat tujuan dari rumahku. Tempat yang selalu ramai dengan kesibukan para pemberi dan pengguna jasa, terminal. Terminal Ciputat. Kalau malam di sini sangat menyenangkan. Berbagai cara digunakan para kondektur demi meraih hati para penumpang, dan si supir juga tak kalah ciamik menggunakan kelihaiannya.
Satu yang pasti, yang masih digunakan sampai saat ini, dengan mengiming-imingi angkutan yang mereka kemudikan akan segera jalan meski sebenarnya kendaraan baru akan jalan setelah bangku terisi semua.
100 meter dari sini terdapat sebuah tempat yang selalu mempertemukan pedagang dan penjual. Bermodalkan koran sebagai alasnya, kursi plastik kecil, dan sebuah lampu bohlam yang disuntik ke satu titik, tiang listrik tentunya, mereka berjuang untuk memperpanjang hidup. Getaran telepon genggamku, telepon genggam dengan teknologi canggih pada zamannya-Nokia 9000, mengalihkan lamunanku.
"Aku sudah sampai."
Sebuah pesan dari dia, perempuan yang kutunggu. Tenguk-tenguk mencari perempuan itu. Mencari sosok perempuan berambut kuncir kuda dengan kaos putih. "Itu dia!!!" Gumamku.
Berdiri tepat di depan ruko yang menjual obat. Di depannya persis berdiri sebuah papan bertuliskan "Apotek Cipoetat 24 jam". Tak lama, aku sandarkan motorku di pinggir terotoar dan aku langsung menghampirinya.
"Hai, Inaya!" Sapaku lebih dulu.
"Eh, Satria?"
Grogi bukan main. Jantungku berdetak lebih cepat, lebih keras. Lututku lemas, dahiku berkeringat tak henti-hentinya. Seakan pori-poriku tak lagi kuasa menahannya.
"Kok, diam saja? Mau di sini aja ngobrolnya?"
Bodohnya, aku hanya diam saja. Tapi mau bagaimana? Belum mampu aku mengatasi gerogiku, dia sudah menembakku dengan sindiran seperti itu. Sekejap aku seperti kena sleep paralysis. Menyedihkan.
"Eh, enggak ko. Bagaimana kalau kita cari makan?"
"Boleh. Aku ikut saja. Terserah," dengan nada lepas dia mencoba mencairkan suasana.
Bila digabungkan memiliki arti Satria yang berjuang dari timur ke barat. Berjuang seperti matahari, yang bergerak dari timur ke barat. Beruntung tidak terbalik, kalau iya, habis sudah.
Aku dilahrikan dari hasil perkimpoian seorang lelaki dan perempuan, ayah dan ibuku. Keluargaku kebutuhannya tercukupi. Alhamdulillah. Sayang, ibuku sudah tiada sejak aku pertama kali teriak di bumi. Beliau meninggal akibat pendarahan hebat saat melahirkanku.
Selama ini, aku hanya mengenali wajah ibuku dari album foto ayah dulu. Ibu sangat cantik. Tak heran bila ayah tergila-gila dengannya. Ayah pandai cari istri, tapi ibu sepertinya kurang.
Ayah banyak bercerita tentang ibu. Ibu adalah adik kelasnya dulu saat mereka mencicipi bangku sekolah atas. Awal pertemuan mereka ketika ada sebuah acara tahunan di sekolah.
"Ibumu itu perempuan pintar, juga tak pernah mengeluh. Dia juga lebih hebat dalam urusan agama. Dia juga senang dengan anak kecil," cerita ayah. "Kalau sudah sama anak kecil, sosok aura keibuannya keluar Sat," katanya.
"Suatu kondisi, ia bisa menjadi sosok anak kecil yang periang, selalu tersenyum. Kondisi lain, ya itu tadi, bisa jadi keibuan."
Lanjut ayah, "kamu tahu tidak Sat? Ibumu biar cantik-cantik begitu, kelakuannya menyebalkan. Kalau ayah coba ajak bicara berdua, jawabnya enggak pernah serius. Selalu saja ngawur. Tapi yang begitu itu, yang bikin ayah jatuh cinta sama ibumu," cerita ayah saat aku baru menginjak umur 17 tahun.
Aku senang kalau ayah cerita soal ibu. Aku ingin merasakan belaian lembut ibu. Meski kini aku sudah rasakan kasih sayang ibu. Ibu tiri. Tapi dia baik, tidak seperti ibu tiri bawang merah-bawang putih.
Ayah menikahinya 10 tahun lalu. Ayah sadar, dirinya dan aku, anak satu-satunya, butuh sosok seorang ibu. Ibu tiriku, eh, aku lebih suka menyebut ibu baruku, perempuan yang tak kalah hebat juga. Dia benar-benar tulus mencintai ayah dan aku. Dia juga tahu latar belakang keluarga kami.
Kamu tahu tidak? waktu itu aku pernah tertangkap basah menonton film dewasa saja, ibu tidak marah. Bahkan dia menawarkan untuk menonton bersama. Tidaklah, aku berbohong. Ibu marah besar, terlihat dari matanya. Aku takut bukan main. Tapi dia mampu mengontrol kemarahannya jadi suatu yang bijaksana.
Dari situ aku sadar, marah itu memang mudah, tapi mengontrolnya menjadi sesuatu kebijaksanaan dan berbuah positif itu yang sulit. Tapi ibu bisa, keren.
Itulah hebatnya ayah, selalu saja bisa mengambil hati perempuan hebat dan membuat perempuan itu menerima segala kekurangan ayah, terutama keluarganya.
***
"Kita mau makan di mana?" tanya Inaya sambil mendekatkan mulutnya di kupingku.
Malam itu, aku dan Inaya, berboncengan mencari tempat makan. Walau sebenarnya aku sudah makan tadi sore, jadi belum terlalu lapar, enggak tahu kalau Inaya.
"Bagaimana kalau makan angkringan di ujung perempatan sana, Angkringan Ibu Lulung?" tanyaku balik
"Terserah, apa saja," jawab Inaya.
Astaga, kenapa aku ajak makan di sana? Mana mungkin aku ajak perempuan ini ke sana. Mana mau dia. Ah, aku lagi-lagi salah langkah. Tapi sudahlah, aku sudah tanya seperti itu. Lagipula dia sudah mengiyakan.
Sesampainya di tempat makan itu, aku parkir motor kesayanganku ini tepat di samping gerobak angkringan. Malam itu tidak terlalu ramai, maklum saja, di zaman seperti itu, tidak banyak orang-orang keluar rumah, beda seperti sekarang.
Lantas aku langsung memilih beberapa jenis makanan yang tersedia di sini. Kebetulan, masakannya baru matang semua, jadi masih hangat. Aku ambil piring, aku pilih nasi bungkus, usus tusuk dua, tahu isi dua, dan minumnya es jeruk. Sedangkan Inaya, hanya pesan satu es teh manis.
"Kamu engga pesen makan Inaya?" tanyaku heran.
"Enggak sat, kebetulan aku sedang tidak nafsu makan, cuma haus," jawabnya santai sambil tersenyum.
Aku terperangah. Bibir mungil berwarna merah melebar tersenyum. Lekukan kedua pipinya presisi indah. Pipinya mau tak mau menjadi membulat lembut.
"Kenapa ih, kok liatinnya gitu?" sentak tanya Inaya padaku.
"Eh, engga. Engga Nay" Ah, sial. Senyuman itu membuatku lupa darat.
Dia dua bersaudara. Adiknya perempuan, lima tahun di bawahnya, kuliah di luar negeri katanya, di Australia. Ia tadinya juga sempat
ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, tapi batal. Enggak tahu kenapa, aku enggak tanya, sungkan. Aku ini kenapa sih? Selalu saja
sungkan untuk bertanya, huh!
Tapi dia sekarang sedang melanjuti kursusnya, kursus desainer. Sambil menggeluti karir juga, yang berhubungan dengan desainer. Betul! Aku enggak nanya di mana, karena sungkan.
Waktu itu, belum banyak profesi desainer, terlebih lagi perempuan. Dulu, kalau mau cari sarjana akuntan, atau teknik banyak, tapi belum banyak desainer.
Aku jadi menyesal sendiri kuliah jurusan perbankan. Apa aku pindah saja ya jurusan desainer seperti Inaya? Itu kan keren, pasti dicari banyak perusahaan. Ah! Tapi aku mana bisa menggambar.
***
Setelah aku mengantar Inaya pulang. Aku hanya terlentang lemas di atas kasur. Kemudian aku menyalakan telepon genggamku yang sejak tadi aku matikan. Sejak aku menyandarkan motorku untuk menghampiri Inaya tepatnya.
Tak lama, telepon genggamku bergetar-sengaja memang aku pasang mode getar, sudah gitu aku matikan pula. Siap betul aku merencanakan ini semua-dan ada 4 New Message terpampang di layar. Aku buka pesan itu. Nama ayah menjadi urutan paling atas di antara tiga pesan lainnya.
Aku berpikir kalau Ayah tadi mencoba menghubungiku, namun tidak aktif, maka Ayah mengirimiku pesan singkat: "Satria, kamu di mana? Ayah telepon sulit sekali dihubungi? Ayah titip ambilkan pesanan ayah di tempat kemarin." Ya ampun, ayah ternyata titip ambilkan berkas-berkas pekerjaannya di tempat kemarin. Aku melirik jam tanganku, ternyata sudah jam 11 malam. Percuma aku ke sana juga pasti tempat itu sudah tutup.
Ayah baru-baru ini baru membuka sebuah kantor bersama-sama rekan kuliahnya dulu. Tempatnya tidak terlalu jauh, hanya butuh sekitar lima menit dari rumah. Ayah dan teman-temannya, paman Gino dan paman Indra, membuka jasa konsultan pembangunan. Aku tidak terlalu paham, tapi setahuku mereka jadi tempat konsultasi untuk para pebisnis yang ingin membangun sebuah gedung atau juga infrastruktur baru. Kebanyakan pemerintah daerah atau pusat jadi klien mereka.
Kutekan tombol panah ke bawah, ada pesan lanjutan dari ayah: "Tadi ada telepon ke rumah. Dia titip salam katanya."
Sontak aku terdiam. Pikiranku kembali kosong. Semuanya terasa lambat, waktu seakan membeku. Dada mendadak sesak. Aku tidak tahu harus bebicara apa, semua terasa menumpuk penuh, tetapi bukan kegelisahan akan sesuatu yang menyakitkan, melainkan rasa yang tak biasa kurasa. Perasaan ini terasa asing bagiku. Mungkinkah dia yang menghubungiku ke rumah?
Mendadak aku menjadi lelaki yang (semakin) pengecut. Tiga pesan berikutnya tak berani aku buka. Tiga pesan itu dari Annisa.
***
Annisa Tunggal. Dari namanya jelas, ia anak satu-satunya, sama sepertiku. Aku mengenal Annisa tiga tahun lalu, saat kita masih sama-sama berseragam SMU. Dia adik kelasku, perbedaan umur kita hanya terpaut satu tahun. Pertama aku melihat dirinya, aku benar-benar terperangah dibuatnya. Cantik wajahnya semakin sempurna dengan lesum pipitnya serta sejentik nevus pigmentosus, atau kalau orang kita bilang tahi lalat di dagu sebelah kanannya. Dan jangan berharap kalian sadar kalau dirinya sudah tersenyum manis, bidadari surga pun akan dibuatnya cemburu. Ditambah, mahkotanya yang akan selalu ditutupi selembar kain dengan syar
Inaya perempuan yang selalu terbuka dan sangat mudah bergaul. Dia sangat mengerti setiap jenis laki-laki, dan tahu bagaimana masuk ke dalam kehidupan laki-laki tersebut, aku contohnya. Dia tahu aku tak terlalu mudah bergaul, terutama dengan perempuan. Ini untuk kali pertama aku kenal begitu dekat seorang perempuan dalam hitungan minggu.
Aku dan Inaya hampir empat kali seminggu bertemu. Setiap bertemu kami memang tak pernah janji di luar, selain karena aku mencari aman, Inaya pun banyak kerjaan yang harus diselesaikan di rumahnya sekaligus kantornya.
Setelah jam pulang kuliah, aku bergegas memacu sepeda motorku. Aku menggilas jalanan dengan kecepatan cukup tinggi, dengan lantang. Aku menabrak panasnya siang itu. Dalam perjalanan aku mencoba mengingat-ingat hubunganku dengan Annisa. Kebaikan serta kepeduliannya sepertinya mulai luntur, tinggal sebatas kabut. Kabut yang tak pernah tergenggam. Aku mulai berkilah: aku ini kan hanya kagum, bukan cinta. Beda dengan rasaku kepada Inaya. Aku ini tahu betul kalau aku benar-benar cinta.
Tak bagus lagi, tak indah lagi cintaku dengan Annisa seperti dulu. Kini aku punya cinta yang lain, Inaya. Inaya Suka Cita Putri. Nama yang selalu aku sebut, wajah yang selalu hadir di langit-langit kamar saban malam tiba. Lama sekali. Terasa lama. Padahal aku sudah menarik kecepatan sekencang mungkin.
Lampu merah terasa begitu lama.
"Hijau!!!"
***
Sesampainya aku di rumah Inaya. Dia tak di tempat. Aku harus menunggu di dalam kamarnya-sekaligus ruang kerjanya-sambil melihat-melihat hasil storyboard yang sejak kemarin dia bikin.
Susunan gambar-gambar yang menceritakan sebuah keluarga sederhana. Keluarga dengan keadaan sosial menengah ke bawah yang masih harus merasakan kepahitan hidup. Tapi sepertinya belum selesai gambar-gambar ini.
"Ini dek, silahkan diminum," ucap perempuan paruh baya tiba-tiba. Mungkin pekerja rumah tangga di rumah Inaya.
"Tadi non Naya titip pesan, katanya suruh tunggu saja. Sebentar lagi pulang," ucapnya.
"Iya bu, terima kasih banyak. Semoga tidak merepotkan," kataku.
Tak lama kemudian, Inaya pulang. Masuk ke sini, ke kamarnya, dengan tergesa. Dahinya menerjunkan setetes keringat yang mendarat di leher. Aku menebak dia berlari dari ujung jalan sana. Karena takut aku menunggunya terlalu lama. Padahal tidak juga. Cuaca di luar memang sangat panas. Jangankan berlari, berjalan sedikit saja sekujur tubuh kalian harus rela dibasahi keringat. Tapi satu hal pasti aku sadari, dia begitu antusias dengan kedatanganku hari ini. Aku semakin senang.
"Kamu sudah lama ya Satria? Aduh maaf, maaf banget. Tadi aku mendadak harus ke tempat kerjaku, ada perubahan jadwal. Aku juga tidak sempat mengabarimu. Maaf, maaf banget," sambil bersandar di depan pintu kamarnya dia berkata demikian dengan nada terengah-engah.
"Engga kok Inaya, Aku baru sebentar di sini. Itu lihat saja, air minumnya masih belum aku minum.
"Ah, sukurlah Satria," masih dengan nada terengah-engah.
Tak lama Inaya melempar beberapa buku tebal dan tasnya ke atas kasur yang dari tadi digendongnya sambil berkata, "Aku mandi dulu ya Satria. Sebentar."
Sembari menunggu Inaya, aku duduk di kursi goyang yang letaknya persis di sebelah lemari foto. Aku duduk sambil ku dongakkan kepalaku ke atas. Aku mendiam. Aku melamun. Tak ingat lagi apa yang aku pikirkan waktu itu. Tak sadar pun aku tertidur di kursi goyang itu.
Baru beberapa menit aku tertidur, tiba-tiba aku seperti melihat seorang wanita, wanita cantik yang benar-benar belum aku lihat selama ini.
"Itu Inaya," hatiku memastikan. "Bukan, itu bukan Inaya. Mana mungkin Inaya berpenampilan seperti itu," hatiku membantahnya.
Tidak, ini pasti mimpi. Tidak, aku sadar. Benar-benar sadar. Jelas sekali, sangat jelas. Aku harus bagaimana ini? Apa aku harus pura-pura tidur saja? Baiklah aku pura-pura tidur saja. Tidak, tidak bisa. Mataku tak bisa aku pejamkan. Aku penasaran.
Inaya???" tegurku dengan penuh rasa tanya.
"Eh, kamu sudah bangun?," sambil berjalan ke arahku.
Betul, ternyata itu Inaya. Aku tidak berada dalam mimpi. Ini realita. Ini nyata. Inaya hanya menggunakan pakaian dalamnya datang ke arahku. Aku mencoba beranjak dari atas kursi goyang. Belum juga badanku berdiri tegap, Inaya mendadak memelukku erat-erat, mencium bibirku. Aku tak kuasa menolak. Hasratku sebagai seorang lelaki tak bisa lagi dibohongi. Kami bercumbu di atas ranjang penuh sensasi. Aku hanya bisa pasrah, dengan apa yang dilakukannya. Inaya seperti menemukan dirinya. Tapi ini bukan seperti Inaya yang aku harapkan. Aku benar-benar terjelembab dalam dan nafsu. Aku tak bisa seperti ini.
Dengan kedua tangannya dia mencoba melucuti bajuku. Tak henti-hentinya kami berciuman. Napasnya ku dengar semakin membara. Napasnya semakin hangat. Aku bisa merasakannya, betul-betul merasakannya. Dia paham betul bagaimana Dia berbisik. Dia tahu kapan harus mendekapku erat-erat, dan melonggarkannya. Dia juga tahu kapan dan di mana dia harus menyentuhku. Aku belum bisa sepenuhnya lepas dari belenggu ini. Aku tidak bebas, meski aku kini melayang dibuatnya.
Tapi ini seperti membawaku ke surga. Aku merasakannya. Seperti pejuang dengan perjuangannya. Seperi penguasa seperti kekuasaannya. Serta lelaki seperti kejantanannya. Merasakan terbang di pelataran surga yang luas beserta se-isi sejuta tanaman dan bintang. Ini bukan sebuah takdir. Ini adalah kecelakaan moral paling dahsyat yang disebabkan didobraknya segala batasan-batasan nurani.
Aku tak bisa begini terus-terusan. Ini menyikasaku. Aku harus melupakan ini, tapi bagaimana caranya? Aku tidak mungkin mengkhianatinya.
Aku tak pernah lihat Annisa hancur, sehancur ini. Dia adalah perempuan yang selalu pintar menyembunyikan kerisauan, kecemasan, dan kekhawatirannya, terutama di depanku. Sekarang, detik ini juga, sekujur tubuhnya gemetar tak kuasa menahan.
Aku masih ingat, saat paman Lukman bilang, kalau Annsisa adalah perempuan kuat dan tak pernah mengeluh. Kini, kini tembok itu runtuh, porak-porandah. Luluh lantah tersisa debu di dasar tanah hanya dalam sekian waktu. Semua berubah menjadi hari di mana dosa besar yang pernah ku perbuat.
Tetes air mata jatuh ke pundak, perlahan dia memegang bahuku, dan berkata: "Aku masih dan akan tetap menjaga kertas ini. Kertas yang pernah kita tulis ini."
"Ada hal di mana aku harus mengikhlaskan dan di mana ada hal yang harus aku perjuangkan. Ikhlas dengan apa yang pernah terjadi, dan perjuangkan apa yang telah kita tuliskan ini, Satria," ucapnya sesenggukan.
Tetes air mataku, diusap dengan kedua tangannya. Aku tidak bisa berkata sepatah kata pun untuk menjawabnya. Annisa benar-benar perempuan kuat.
***
Sejak saat itu ada rasa penyesalanku yang begitu mendalam. Namun justru itu yang membuatku untuk menjaga diri agar tak berbuat nyeleweng lagi. Annisa juga tidak pernah membahas kejadian itu lagi sedikit pun.
Aku mengerti, membahas kejadian itu hanya akan menambah masalah saja dan mengorek luka lama. Dan karena kepercayaannya yang masih begitu besar kepadaku, maka tepat hari ini, 27 November 1996, aku beranikan diri untuk menikahi perempuan hebat itu.
Terima Kasih, Annisa atas kepercayaanmu yang luar biasa besar.
Tamat
- Merdeka.com tidak bertanggung jawab atas hak cipta dan isi artikel ini, dan tidak memiliki afiliasi dengan penulis
- Untuk menghubungi penulis, kunjungi situs berikut : ibnu-siena
-

Kucing Oren Manjalita, Ngga Mau Makan Kalau Ngga Dipuji dan Disuapin
-

Anji*ng di Nikahin, Pakai Upcara Adat, Habis Biaya Ratusan Juta
-

Ngakak Abist, Momen Mahasiswi Nagku Sok Sok an Rajin di Daily Vlog Diketawain Sama Uminya
-

Bikin Kaget dan Terkejoet, Lukisan Corat-Coret Karya Pelukis Ini dihargai Rp 14,5 M!
KOMENTAR ANDA
Artikel Lainnya
-

-

Pertama Kali Lihat Pengamen, Pace Asal Suku Dani Papua Ini Keheranan
21 Juni 2023 19:33 -

-

-

Gokil Bin Viral, Mulung Barang Bekas Dapat iPhone 12 Pro Dong
19 Juni 2023 14:11 -

Cara Agar Sepatu Tidak Licin Di Lantai Tanpa Ribet
6 Juni 2023 20:31 -

Rahasia Artis Senior Widyawati Selalu ampil Cantik dan Percaya Diri di Usia Lanjut
13 Desember 2022 21:28 -

Deretan Potret Gaya Terbaru Risty Tagor yg Disebut Netizen Tidak Tampil Syar'i lagi
8 November 2022 09:21 -

Ciptakan Rasa Otentik, RM Padang Payakumbuah Semakin Populer
18 September 2022 07:25 -











Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.